"gimana jo?" ujarnya sembari memalingkan mukanya ke jalanan.
"Gimana apane rur?" sedikit mengernyitkan alis, mengambil tempat di sebelah orang yang memanggilnya 'jo'.
Bukannya
menanggapi kawannya tadi, Pahrur ini cuma tersenyum lihat jalanan
sibuk. Jarum kecil jam tangannya saja sudah enggan nunjukin angka
sebelas.
"Leganya, sudah jam sebelas saja rur. Selonjorin kaki dulu, sana agak kesana dikit napa"
Dirogohnya saku belakang jins kumal, dan mendapati sebatang gulungan tembakau berlabel 'inovativ' pakai huruf 'v' dibelakangnya.
"Jadi orang kui rur, kayak rokok ini. Inovativ. Sama kayak mobil yang lewat-lewat itu rur."
Jengkel
karena yang diajak ngomong dari tadi malah melototin jalanan yang
sumpek itu, dia menyulut gulungan tembakau itu. Diolesinya dengan lethek
kopi.
"Bahkan menulisnya pun salah, Jo. Itu huruf terakhirnya
pakai 'f'' bukan 'v'. Kita orang Indonesia, Jo. Beda juga sama mobil
yang lewat itu. Cuma sekedar merk." yang diajak ngobrol akhirnya
menimpali.
"Karepmu rur. Maksudnya yang buat rokok kan kayak gitu
juga. Dari SD dia sudah nggulung kali, ndak pernah dia tahu apa itu SMP
itu. Ya kayak aku gini to rur." dia tersenyum, senyum kecut.
Pahrur ikut-ikutan tersenyum.
"Kalau
saja orang-orang penting negara ini berpikiran begitu. Maksudnya buat
yang terbaik tanpa berpikir apa prosedurnya, gimana caranya, yang
penting hasilnya. Andai saja ya jo."
"ya gak bisa gitu rur,
kacau nanti negara ini. Lha wong, semua jadi seenaknya sendiri tanpa
aturan." ujarnya sambil perlahan mengisap asap gulungan tembakaunya agak
menjauh dari kawannya. Dia tahu betul sebenarnya kalau kawannya tidak
suka dengan yang namanya rokok, bukan karena asapnya, karena suatu
alasan sentimentil. Setiap ditanya, "hanya masalah prinsip jo. Kalau
kita nggak punya, apa jadinya kita. Hanya bangkai berbau busuk tiap kita
ngomong.". Dia mafhum akan hal itu.
"Lihatlah itu jo, semua yang berlalu lalang berpikir seolah
urusan merekalah yang paling penting. Melebihi urusan negara ini.
Lihatlah, saling sikut tak peduli yang disikutnya ibu yang sedang
menggendong anaknya yang kritis mau dibawa ke UGD. Semua merasa
penting."
Rejo berhenti mengisap rokoknya sejenak, menajamkan penglihatannya ke arah jalanan.
"Ah
itu kan sama saja kamu, kalau pagi-pagi sudah mau jam setengah lapan.
Takut gajimu dipotong. Aku aja sudah ngobrol sama Pak Haji di serambi
Musholla pas kamu masih ngiler di bantalmu. Baik rur Pak Haji itu di
tempat kayak gini."
"Ibu itu gak pernah berpikir bakalan ditolak bayinya, yang dia
tahu hanya bagaimana senyum anaknya di setiap pagi tetap terkembang. Ah,
negara ini ya jo."
"Mau bagaimana lagi rur. Dulu emakku gak pernah pusing soal tetek
bengek Jamkes atau kartu sehat atau apalah itu. Aku dulu setep ya
dibawa ke Lek Parjan."
"Simpel ya jo Mak Rukmi itu."
"Ya mana bisa rur, emakku suruh ngisi kertas-kertas itu. Coba tanyain
uleg uleg, harga cabe sekilo, atau dimana dapat daun kenikir paling top,
dia jagonya."
"Haha, paling top dah itu pecelnya. Tapi kalo lihat
politisi-politisi itu ngomong di radio kesayangannya, dia pasti sudah
maki-maki. Aku saja yang lagi enak-enak sarapan, ikutan disembur"
"Begitulah emakku rur. Paling top. Kayak paling tahu urusan
negara ini saja. Padahal dia cuma alergi sama omong kosong, rur.
Hahaha.."
Kedua kawan itu sekonyong-konyong tertawa bersamaan. Mengalahkan
riuhnya jalanan. Mak Darti, yang punya warung, hanya geleng-geleng lihat
keduanya. Seorang adalah kuli bangunan di proyek sebelah warungnya,
meski ngutang kalau makan tapi pasti lunas setiap gajian. Anehnya, dia
lebih suka ngutang daripada ditraktir kawan di sebelahnya. Bukan gengsi,
biar ada semangatnya kalau kerja. Satunya lebih aneh lagi, ngakunya PNS
tapi gak pernah pake seragam abu-abu atau batik korpri yang biasa dia
lihat kalau ada PNS yang ketahuan mangkir di televisi. Keduanya seolah
orang paling pinter di negara ini, pikir Mak Darti.
"Jo, senang pasti rasanya kerjaanmu seharian sudah kelar. Tinggal
selonjoran di warung Mak Darti. Ya kayak gitu jo, pas dulu waktu aku
selesai sekolah terus bantu angkat-angkat barang di Toko Haji Marno.
Sorenya, sambil nunggu magrib sudah dibuatin masakan ibu, tinggal
selonjoran sama kamu di sebelah rumah."
"Rur..rur..sawang sinawang. Kamu itu lho kurang apa. Gaji sudah lumayan. Dapat pensiun. Kawin wae sana."
"Begitulah jo. Kadang bukan seperti itu yang dicari. Nggak nyaman
jo, dituntut sana sini, bosnya begini, aturannya begitu. Orang ini
dilayani begini lainnya begitu. Apa aku bakar saja kantorku itu ya jo?"
"Haha..gendeng kamu rur."
Keduanya tertawa lagi. Malam itu anak-anak brilian beda nasib saling
menyeduh kopinya. Seolah apa yang mereka bicarakan tak kalah seru dengan
sekumpulan orang berpakaian parlente di gedung bundar itu. Bedanya,
mereka nggak sampai jotos-jotosan kalo berdebat.
Popular Posts
-
here I write (again)...! Tidak ada puisi-puisi absurd dan kata-kata yang tak jelas artinya. Tidak kali ini. Sedikit perspektif berpikir ya...
-
“Gus, kita tukeran ya? Kan gak bisa kalau satu sekolah ada 2 profesi yang sama.” Sesama fiskus se-almamater meminta saya beberapa wak...
-
“Hipokrit dan apatis ah kakak!” teriak ruri cengengesan semari berjalan menuju dapur. Gadis 5 tahun ini baru saja belajar -atau lebih te...
-
Team!!! Demikian mungkin judul yang cocok untuk trip kali ini, bersama presiden Sengak Simbah , wakil presiden PHP Bai , Si...
-
Ketika terlintas kata ‘Buku’, yang terpikirkan oleh Antok adalah barang mahal kecuali buku pelajaran wajib dari sekolah atau lebih di...
-
" Di negeri para bedebah, kisah fiksi kalah seru dibanding kisah nyata. Di negeri para bedebah, musang berbulu domba berkeliaran di ha...
-
" g imana jo?" ujarnya sembari memalingkan mukanya ke jalanan. "Gimana apane rur?" sedikit mengernyitkan alis, mengam...
-
Tuhan Bukankah kami dicipta untuk kembali padaMu? Bukankah dunia bekal kami untuk itu? Bukankah Tapi saya, oh Tuhanku, terlintas pemaham...
-
Kembang api, simbolisme terkait erat dengan perayaan Hari pertama setiap tahun masehi , sering kita peringati sebagai tahun baru. M...
-
Siang itu, shaf-shaf masjid masih penuh di bagian dalam ruangan utama masjid di kompleks kantor. Imam sholat mulai beranjak dari dudukn...
Blogger templates
Follow us at FB
tukang coret-coret
halamannol. Diberdayakan oleh Blogger.
Copyrights @ Journal 2014 - Designed By Templateism - SEO Plugin by MyBloggerLab



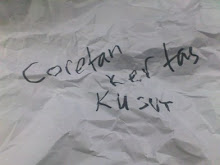
Kenapa mas nggak nyoba nulis novel aja?
BalasHapusada bakat nulis jangan disiakan lah..
:)))
wah maksih banyak mas, tapi berlebihan sampe novel segala
BalasHapusIni tulisan, cocoknya di kertas bungkus kacang, yg daripada dibuang mending jadikan bungkus kacang. :)